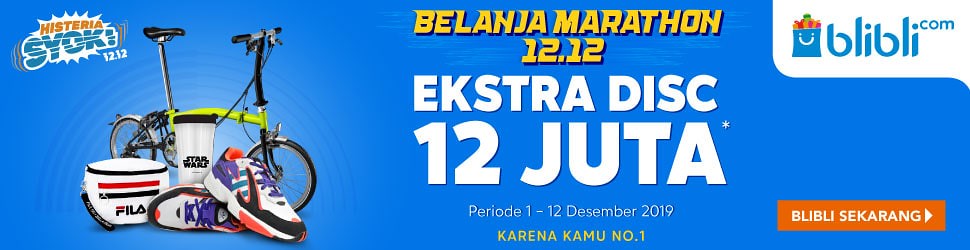Oleh: Abdul Ghopur
Tidaklah berlebihan mengatakan bahwa tidak mudah memimpin sebuah negara yang sedang dalam era perubahan, era transisi demokrasi, yang masyarakatnya juga masih dalam euphoria. Seperti yang terjadi di negeri kita sejak hadirnya era reformasi. Yaitu, era yang ditandai dengan terjadinya perubahan konfigurasi masyarakat yang semakin bebas dalam mengekspresikan gagasan, pikiran, dan bahkan ‘emosi’-nya. Terlebih di era ini, dengan telah beberapa kali diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden semakin banyak dibatasi dan atau dibagi dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Presiden bukanlah penguasa yang full power lagi, seperti di era sebelumnya.
Kebebasan dalam berdemokrasi sempat dimaknai dan diaktualisasikan dengan bias oleh sebagian masyarakat kita. Kebebasan berbicara (freedom of speech) di ruang publik bukan hanya menjadi ajang kebebasan berpendapat, tetapi juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk ajang hujat-menghujat, cela-mencela, berolok-olok, dan tidak jarang berupa tebaran fitnah. Sementara kebebasan berbuat (freedom of action) bukan hanya menjadi ajang kebebasan aksi demonstrasi, melainkan juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk aksi menjarah dan aksi kekerasan lainnya. Tidak jarang, implementasi freedom of action juga menimbulkan korban sia-sia dengan rusaknya berbagai fasilitas umum dan menghadirkan kerugian banyak finansial, bahkan juga ada korban nyawa manusia. Oleh karena itu, kita juga merasakan hadirnya sebuah era ‘politik gaduh’ yang tidak saja sering membingungkan, tetapi juga merisaukan. Dalam ruang sosial-politik gaduh, muncul pula tindakan sekelompok masyarakat yang tidak tabu lagi mendesakralisasi makna, filosofi dan simbol-simbol negara, seperti gerakan anti NKRI dan Pancasila, dengan mengatakan NKRI dan Pancasila adalah Thogut.
Keadaan semacam inilah yang dewasa ini dihadapi dan dirasakan oleh rakyat Indonesia terutama para pemimpin bangsa di era reformasi ini. Jika situasi dan kondisinya belum banyak berubah, bukan hanya persoalan manajemen kenegaraan semata yang mereka hadapi, melainkan juga persoalan perubahan perilaku sosial, sebagai bagian dari dampak euphoria reformasi dan transisi demokrasi.
Dalam fenomena semacam inilah saya merasa kita sangat membutuhkan gagasan bernas dan genuine tentang apa makna sesungguhnya demokrasi ala’ Indonesia kepada kita. Dengan referensi nilai-nilai yang sangat memadai dari beragam sudut pandang termasuk pandangan Islam dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Sehingga, demokrasi jangan dipahami sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas dan rambu-rambu. Demokrasi bukan semata-mata menekankan pada aspek prosedural dan tidak berorientasi pada pengembangan nilai-nilai luhur serta tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Prinsip demokrasi haruslah mampu menjaga keutuhan bangsa, menciptakan keadilan dan memberikan kesejahteraan pada rakyat, menjaga kebersamaan dalam keBhinnekaan, memperhatikan prinsip permusyawaratan/perwakilan dan kemufakatan yang mencerminkan keragaman bangsa dan tidak semata-mata berdasarkan mekanisme pemilihan (one man one vote), serta menjamin kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demokrasi bukan menang-kalah, bukan kuat-kuatan, bukan menang-menangan. Tapi, demokrasi itu mau mendengar orang lain dengan sinergitas untuk mencapai visi besar bersama bangsa. Demokrasi yang paling murni adalah apa yang kita miliki, yaitu musyawarah-mufakat. Dan, keputusan yang telah diambil secara bersama tak boleh dikutik-kutik (tidak diganggu-gugat).
Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika seluruh masyarakat baik elit dan akar rumput serta seluruh stake holder demokrasi mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Di samping itu demokrasi akan berjalan baik dan benar manakala masing-masing orang bersikap amanah, tau diri, dan mau mengerti satu sama lain, serta harus belajar untuk tidak saling intervensi dan belajar memperkuat posisinya masing-masing. Situasi demokrasi Indonesia yang tengah diusahakan kea rah yang lebih baik dan substansial harus tetap dipertahankan dan senantiasa dilestarikan selama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa. Karenaya pembagian tugas pokok fungsi demokrasi harus sesuai dengan peran, kewenangan dan keahliannya menjadi penting. Dus, situasi dan praktik demokrasi di Indonesia belum bisa istiqomah (konsisten).
Dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia telah mengalami banyak pergeseran seiring dengan perubahan sistem pemerintahan negara. Sejak dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950 hingga 1959, praktik demokrasi bergeser ke arah demokrasi liberal-parlementer. Namun, di sisi lain, kebebasan berpendapat malah disumbat. Alhasil, era demokrasi Pancasila telah berakhir bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan lahirlah Orde Reformasi. Demokrasipun kembali bergeser sejalan dengan perubahan sistem dan kebijakan.
Di era Reformasi, prinsip kebebasan mendominasi wacana publik. Berbagai narasi tentang kebebasan dan keterbukaan mendominasi wacana publik tentang demokrasi. Pada titik ini demokrasi telah terkoreksi, nilai demokrasi sekadar dimaknai sebagai sebuah kebebasan seluas-luasnya. Elit politik lebih menyukai demokrasi one man one vote yang kerap mengedepankan voting dengan suara terbayak. Akibatnya, seperti saya sebutkan tadi, demokrasi telah bergeser menjadi ajang caci maki. Bahkan lebih tragis, nilai (value) demokrasi berubah menjadi nilai (nominal) atau yang kerap disebut dengan istilah demokrasi transaksional. Singkat kata, demokrasi saat ini perlu dievaluasi kembali agar tidak kebablasan dan supaya on the track dengan cita-cita reformasi dan sesuai dengan falsafah bangsa.
Oleh karena itu penting seorang yang mengaku demokrat selaiknya memiliki keahlian untuk memikul tugas dan peran kesejarahannya dalam memperjuangkan demokrasi substansial di republik tercinta ini. Menjadi kompas serta khazanah dan pengetahuan demokrasi substansial di era milenial. Sebab, esensi demokrasi adalah kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan demokratis harus berorientasi pada pemenuhan esensi demokrasi itu. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, bukan sekedar menjalankan demokrasi prosedural dengan adanya Pemilu yang secara reguler dan periodik dilaksanakan, tetapi juga semestinya menjalankan demokrasi substansial dengan menghormati hak-hak dasar rakyat sesuai konstitusi.
Idealisme dan usaha tak kenal lelah untuk mewujudkannya–demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan demokrasi Indonesia yang subtansial adalah keharusan. Demokrasi di Indonesia jangan pernah berhenti pada demokrasi prosedural saja, tetapi sungguh mencerminkan hikmat kebijaksanaan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak jaman keemasan Nusantara sudah mempunyai tatanan yang khas dalam berkehidupan bersama, yang sekarang disebut sebagai budaya lokal (local wisdom). Pola berkehidupan-bersama yang harmonis bisa kita lihat pada tradisi guyub khususnya di masyarakat pedesaan, yang mengedepankan kebersamaan, keadilan, musyawarah untuk mencapai mufakat. Local wisdom yang didapatkan di seluruh masyarakat Nusantara yang bersuku-suku dan ras serta agama tersebut, dalam tatanan kehidupan bernegara oleh founding fathers kita diformulasikan dalam salah satu sila dalam Pancasila, yang merupakan dasar kehidupan bernegara yang harmonis dari masyarakat Nusantara yang ber-bhinneka. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan.
Sejarah demokrasi, menyadarkan kita bahwa demokrasi ‘ala Nusantara adalah jalan terbaik. Demokrasi yang bukan berakar dari teori konflik dunia Barat, namun demokrasi ‘ala Nusantara yang bersumber dari teori sinergi sari pati kearifan alam dan budaya negeri ini. Meski perjalanan demokrasi di republik tercinta ini, terkesan kebablasan, sehingga memunculkan ontran-ontran dalam pelbagai lapisan sosial dan menyisakan pertanyaan apakah mayoritas dari kita telah siap mewujudkan demokrasi sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya?
Demokrasi, baik sebagai sejarah ide-ide maupun sebagai praktek politik yang dianut negara bangsa, ternyata masih menyisakan problem besar yang tak kunjung usai. Semua kita selaiknya terpanggil untuk dapat mengambil perannya masing-masing dalam kehidupan berdemokrasi, mengajak para pejuang demokrasi untuk bersikap lebih kritis lagi terhadap demokrasi, khusunya praktek demokrasi di Indonesia. Mampukah Indonesia merevisi ulang demokrasi yang dianutnya?
Sebab, perjalanan panjang demokrasi sejak era Yunani kuno hingga era modern dengan segala variannya, termasuk perkembangannya di Indonesia, kerap mengalami berbagai permasalahan, namun demokrasi masih dianggap dan merupakan sistem yang terbaik dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, belum ditemukan sistem yang lebih baik. Tidak ada sistem pemerintahan di dunia yang sempurna termasuk demokrasi. Sebagai sistem dengan segala kompleksitas latar belakanganya, potret perjalanan demokrasi di Indonesia harus dilihat secara jernih dan obyektif, bahkan beberapa catatan dan analisis mendalam menjadi penting sebagai otokritik bagi penguatan tahapan demokrasi ke depannya.
Penulis adalah Intelektual Muda Ahlussunnah Waljama’ah (ASWAJA),
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB),
Founder Indonesia Young Leaders Forum;
Inisiator Yayasan Kedai Ide Pancasila
(menulis banyak buku dan artikel)
Disclaimer: (makalah ini merupakan pendapat peribadi, orang lain dapat saja berpendapat berbeda)
Referensi:
Abdul Ghopur. 2018. Ironi Demokrasi: Menyibak Tabir Dan Menggali Makna Tersembunyi Demokrasi. Jakarta.LKSB Press. Hlm. vii-xvi.
Abdul Ghopur. 2019. Pancasila Nalar Bangsa: Dalil Dan Dasar (Mengapa) Harus Berpancasila?. Jakarta. LKSB Press. Hlm. 106-132.
Fathoni. 2018. Tirakat KH Hasyim Asy’ari saat Mentashih Pancasila. Jakarta. Fragmen. NU Online.
KH. Ahmad Muwafiq. 2018. Putuskan Pancasila Sesuai Syar’i, KH Hasyim Asy’ari Puasa 3 Hari dan Khatamkan Fatihah 350.000 Kali. Jakarta. www.dutaislam.com.
Dan, dari berbagai serpihan sumber lainnya.